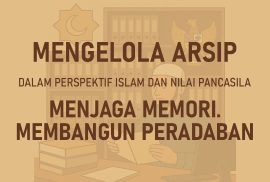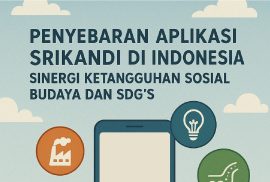Oleh: Nanik Lestari
“Dari ponsel sederhana, warga pesisir Kota Pekalongan menulis ulang sejarah mereka. Merekam memori melalui media sosial menjadi jembatan antara kenangan yang hampir hilang dan masa depan yang masih bisa diingat.”
Transformasi Arsip Media Sosial di Wilayah Pesisir
Setiap kali pasang laut tiba di Kota Pekalongan, air asin menyusup perlahan ke dalam rumah-rumah penduduk. Bagi banyak keluarga, banjir rob bukan lagi peristiwa alam, melainkan rutinitas tahunan. Seperangkat dokumen yang tersimpan personal atau keluarga, instansi bukan hanya rusak tetapi juga lenyap. Padahal, menurut Franks (2018), sejak zaman prasejarah hingga era digital, manusia selalu berusaha mendokumentasikan pengalaman hidupnya menggunakan media yang tersedia sejak dulu baik dari lukisan gua hingga era sekarang yang berbasis digital. Pola ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan rekam jejak tidak pernah berubah, hanya medianya yang berganti.