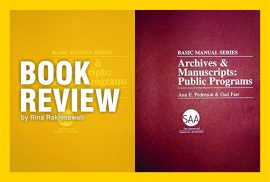artikel
Monday, 8 October 2018
Oleh: Tsabit Alayk Ridholah
Ketika kita mendengar kata arsip, maka pikiran kita langsung terbesit pada tumpukan kertas didalam lemari tua yang jarang dilihat. Ketika kita mendengar kata arsip, maka secara otomatis kita akan mengarah pada kertas usang sebagai bukti administrasi. Padahal, arsip sebagai rekaman informasi tidak layak dan tidak seharusnya diperilakukan seperti itu. Pada zaman sekarang, dimana internet sudah tidak menjadi kepentingan tersier lagi, google dan sosial media adalah konsumsi sehari-hari masyarakat. Memang benar adanya bahwa terkadang kita melupakan arsip milik pribadi, baik itu lupa menyimpan atau bahkan hilang. Namun pada intinya, arsip sangat dibutuhkan. Bahkan jika di level negara, jika arsip vital yang hilang, maka urusannya adalah legalitas suatu daerah, hingga bisa saja diklaim milik negara lain seperti kasus Sipadan-Ligitan. Mantan Presiden Panama, Richardo J. Alfaro mengatakan bahwa “pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat. Arsip memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan bangsa”. Inilah bukti dari pentingnya arsip menurut mantan Presiden yang “arsip” rahasia negaranya terbongkar. read more
 Berawal dengan nama KUNCI Cultural Studies Center, KUNCI adalah kelompok belajar yang dibentuk oleh Nuraini Juliastuti dan Antariksa pada tahun 1999 sebagai upaya untuk membentuk ruang alternatif pasca kejatuhan Orde Baru. Pada praktiknya, KUNCI berperan sebagai pusat kajian budaya nirlaba melalui kerja-kerja penelitian dan publikasi dalam semangat lintas disiplin dan lokalitas seputar seni, budaya dan pendidikan alternatif. KUNCI membayangkan diri sebagai ruang produksi pengetahuan yang berpijak pada kesadaran praksis politik budaya di tengah politik praktis yang berkembang setelah kejatuhan rezim.
Berawal dengan nama KUNCI Cultural Studies Center, KUNCI adalah kelompok belajar yang dibentuk oleh Nuraini Juliastuti dan Antariksa pada tahun 1999 sebagai upaya untuk membentuk ruang alternatif pasca kejatuhan Orde Baru. Pada praktiknya, KUNCI berperan sebagai pusat kajian budaya nirlaba melalui kerja-kerja penelitian dan publikasi dalam semangat lintas disiplin dan lokalitas seputar seni, budaya dan pendidikan alternatif. KUNCI membayangkan diri sebagai ruang produksi pengetahuan yang berpijak pada kesadaran praksis politik budaya di tengah politik praktis yang berkembang setelah kejatuhan rezim.